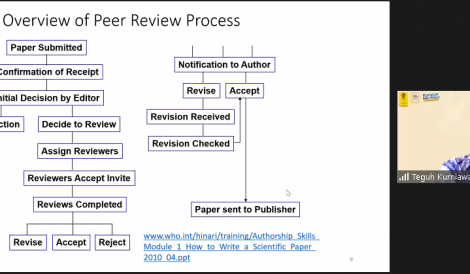Lubang Hitam Otonomi Daerah
Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia sejak Reformasi yang membawa keinginan untuk menata hubungan pusat-daerah sebagai antitesis otoritarianisme, kini justru terdapat pusaran yang mampu menyurutkan praktik otonomi daerah.
Pusaran tersebut terus-menerus membesar, seolah lubang hitam besar yang meluluhlantakkan dinamika ruang otonomi daerah sebagai jalan penataan hubungan pusat-daerah yang diinginkan bangsa Indonesia. Lubang hitam besar itu ditandai dengan dua undang-undang (UU) pengganti UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tonggak masa Reformasi, yaitu UU No 32/2004 dan UU No 23/2014.
Boleh jadi arus otonomi daerah pada masa UU No 22/1999 perlu pembenahan karena ada ”dampak berlebih otonomi” tersebut, tetapi yang terjadi bak pendulum sentralisasi-desentralisasi, bergaung keras kembali ke arah sentralisasi.
Artikel ini menggali praktik otonomi daerah yang perlu diantisipasi karena terdapat berbagai pemahaman yang berpotensi mematikan otonomi daerah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan RI.
Inti pusaran
Beberapa penyebab pembenahan praktik hubungan pusat-daerah di Indonesia sejak tumbangnya rezim Soeharto yang tampak menjadi inti lubang hitam besar otonomi daerah di Indonesia dapat dicatat sebagai berikut.
Pertama, tidak dipahaminya mazhab ero-kontinental yang dipraktikkan di Indonesia dicampurbaurkan dengan mazhab Anglo-Saxon. Penyebab ini menimbulkan adanya praktik pemakzulan (impeachment) kepala daerah. Kisruh pemerintahan terjadi saat itu sehingga muncul pilihan membenahinya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung agar mudah untuk mengurangi wewenang DPRD.
Kedua, tidak dipahaminya penerapan sistem wakil pemerintah yang tetap dianut sebagai turunan dari mazhab ero-kontinental meskipun berhenti hanya sampai gubernur dan kekeliruan memahami makna asas dekonsentrasi.
Sistem wakil pemerintah ini dijalankan dengan dekonsentrasi yang ternyata juga tercampur aduk dengan paham desentralisasi ala Anglo-Saxon. Bupati/wali kota menjalankan urusan PUM yang disebut dalam UU No 23/2014 dengan dasar asas dekonsentrasi, padahal bukan sebagai wakil pemerintah.
Dekonsentrasi juga membawa akibat semua sektor dapat memberikan wewenang kepada gubernur selaku wakil pemerintah yang tercampur aduk dengan daerah provinsi menerima desentralisasi dari urusan sektor sehingga muncul Pasal 10 dan 19 dalam UU No 23/2014 tersebut.
Akibat yang paling menyedihkan, tetap diselenggarakannya dana dekonsentrasi, di mana dana tersebut diatur dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), tetapi dikerjakan oleh daerah otonom melalui gubernur sebagai wakil pemerintah.
Ketiga, sistem pembagian Ultra Vires Doctrine yang membabi buta mencerminkan pemerintah tidak mengenali variasi wilayah RI yang amat heterogen meskipun terdapat urusan wajib dan sukarela. Pemahaman ini diikuti oleh pemahaman bahwa tiap sektor sama dalam derajat penyerahan urusan ke daerah otonom dan dipahaminya antardaerah seolah sama, kecuali dengan otonomi khusus (asimetri).
Dalam hal ini, elemen di K/L menganggap bahwa birokrasi daerah adalah bawahan dari birokrasi pusat. Hal ini dicontohkan sendiri oleh unsur Kementerian Dalam Negeri yang dijustifikasi oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam soal administrasi kependudukan (adminduk).
Seolah berhasil dalam kinerja perihal adminduk, tetapi sesungguhnya meluluhlantakkan praktik otonomi daerah di sini. Celakanya ini berimbas menginspirasi sektor lainnya.
Keempat, sistem pilkada hanya dipahami dari sudut kedaulatan rakyat dengan diacunya pilkada langsung. Sesungguhnya dalam negara kesatuan, otonomi daerah dibatasi atau harus tunduk dengan kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional di negara kesatuan tidak dapat dipecah-pecah.
Oleh karena itu, pilkada, baik langsung maupun tidak, dasar pikirnya adalah akseptabilitas calon kepala daerah, bukan kedaulatan rakyat. Pada level provinsi, gubernur sebagai kepala daerah juga berperan sebagai wakil pemerintah (dual role) karena diacunya prefektur terintegrasi. Pada konteks ini sama sekali tak dilaksanakan makna adanya wakil pemerintah dalam sistem pemilihan gubernur itu.
Kelima, buruknya otonomi daerah dipandang hanya karena elemen internal daerah otonom. Ini tecermin dalam UU Cipta Kerja dan sejenisnya yang menarik kembali urusan yang telah diserahkan melalui desentralisasi ke tangan pemerintah pusat.
Selama ini yang dilupakan adalah adanya gaya ekstrem, dilarangnya elemen pusat beroperasi di daerah akibat pemahaman ketiga di atas, berdampak pada dilarangnya di luar lima bidang adanya instansi vertikal di daerah dibentuk.
Sekalipun berhasil dibentuk, harus diseleksi sangat ketat dan hanya pelayanan yang dibenarkan, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab pula dalam pembinaan pengawasan (binwas) dan pembinaan teknis (bintek).
Dilepasnya daerah tanpa pembinaan tentu menjadi ”berlebih” otonomi daerah tersebut. Binwas dan bintek melalui gubernur sebagai wakil pemerintah adalah pembinaan yang tidak tepat asas. Namun, daerah otonom sudah telanjur disalahkan.
Menguatkan otonomi daerah
Kelima penyebab otonomi berlebih menyebabkan reaksi ada lubang hitam otonomi daerah yang seolah dibenarkan. Diperkuat oleh ada anggapan keberhasilan bahwa birokrasi daerah otonom adalah bawahan dari birokrasi pusat.
Ini pula yang menyebabkan menguatnya istilah ”delegasi” dalam terminologi organisasi mikro ketimbang dalam perspektif pemerintahan negara bangsa (makro) untuk diacu. Keraguan besar adalah menyangkut konsistensi konsep delegasi tersebut. Akibatnya, ruang otonomi di Indonesia, meskipun disertai gegap gempita pilkada langsung, sesungguhnya semakin surut (mengecil), bahkan menuju pudar.
Otonomi desa yang dikuatkan pun akan terimbas dengan pengaturan kecamatan mengikuti lima penyebab di atas. Aturan teknis dalam Kementerian Dalam Negeri sedang menguatkan kecamatan untuk berlaku nasional, menata hubungan kabupaten/kota dengan desa-desa melalui kecamatan sebagai hub.
Jalan perbaikan adanya pusaran mematikan otonomi daerah itu adalah dengan menguatkan kembali otonomi daerah. Tentu dengan jalan yang tak membabi buta. Berkaca pada pengalaman pembenahan masa Reformasi harus dimulai dengan arah yang jelas.
Didasari oleh pilihan mazhab yang kuat, kemudian diturunkan dalam tata cara teknis yang diatur dalam UU pemerintahan daerah kembali secara kuat dan meyakinkan. Peraturan perundangan sektoral harus dibenahi pula dengan berkaca pada lima penyebab di atas.
oleh: Irfan Ridwan Maksum (Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Chairman DeLOGO-Universitas Indonesia)
Dimuat dalam Harian Kompas – Senin, 22 November 2021